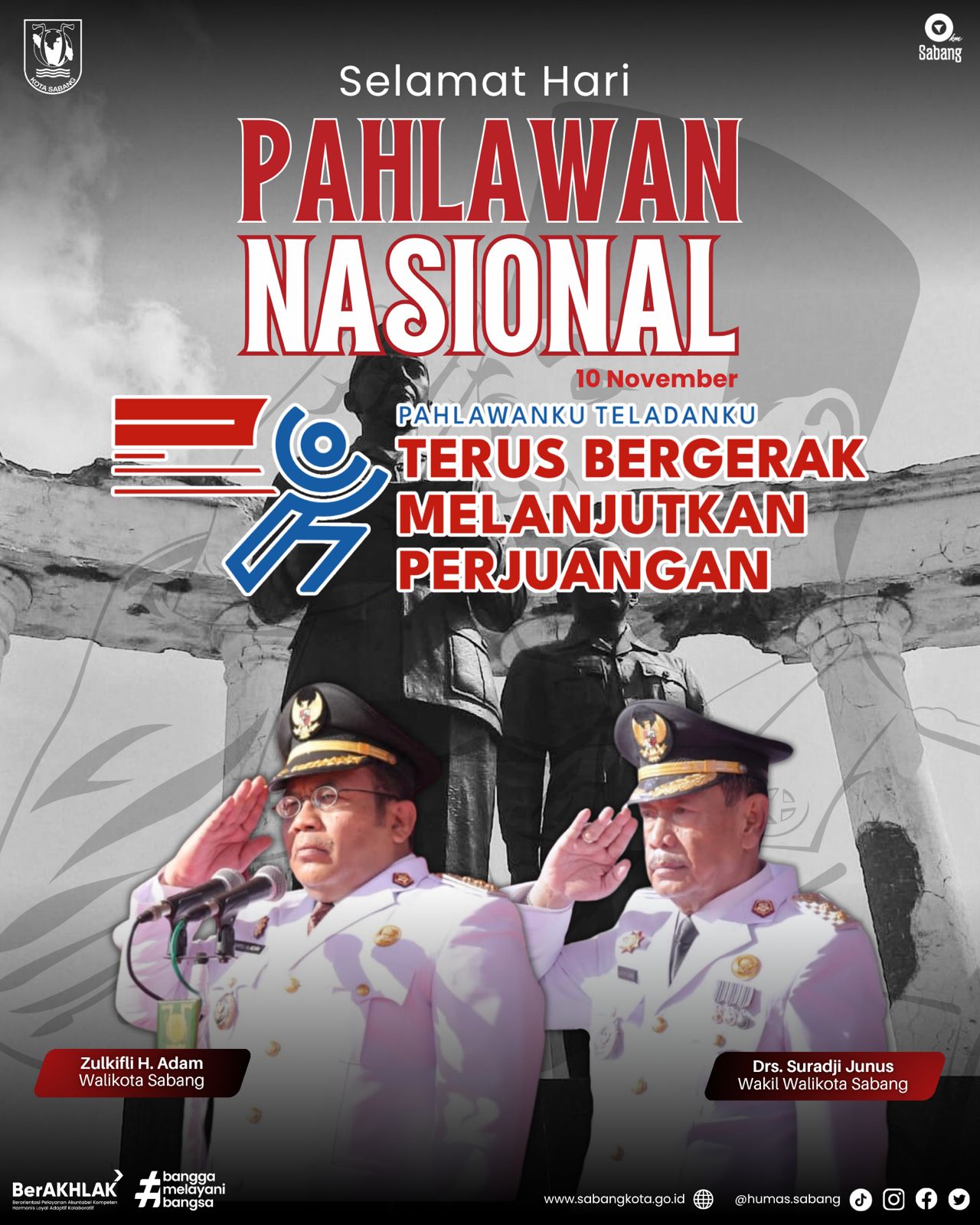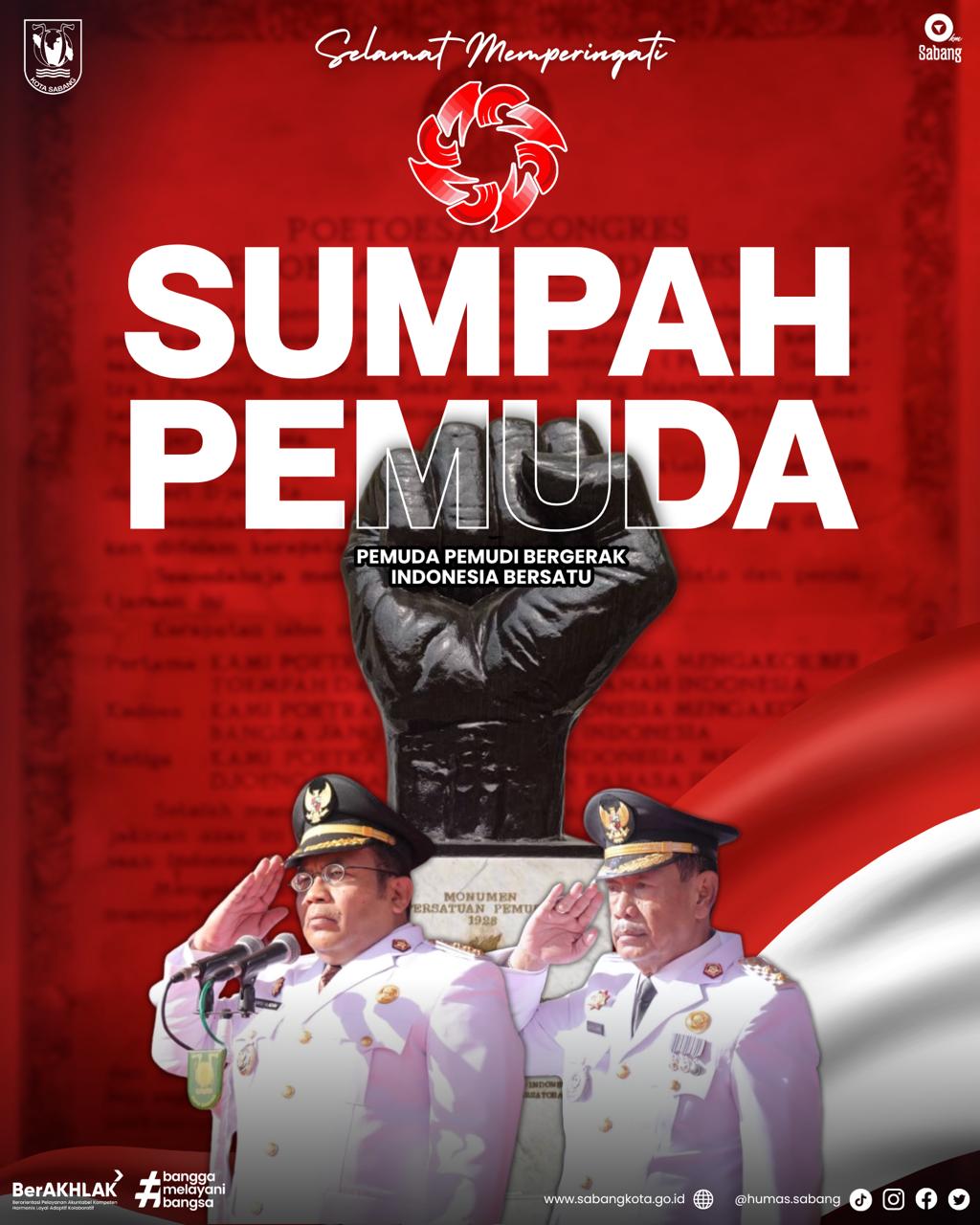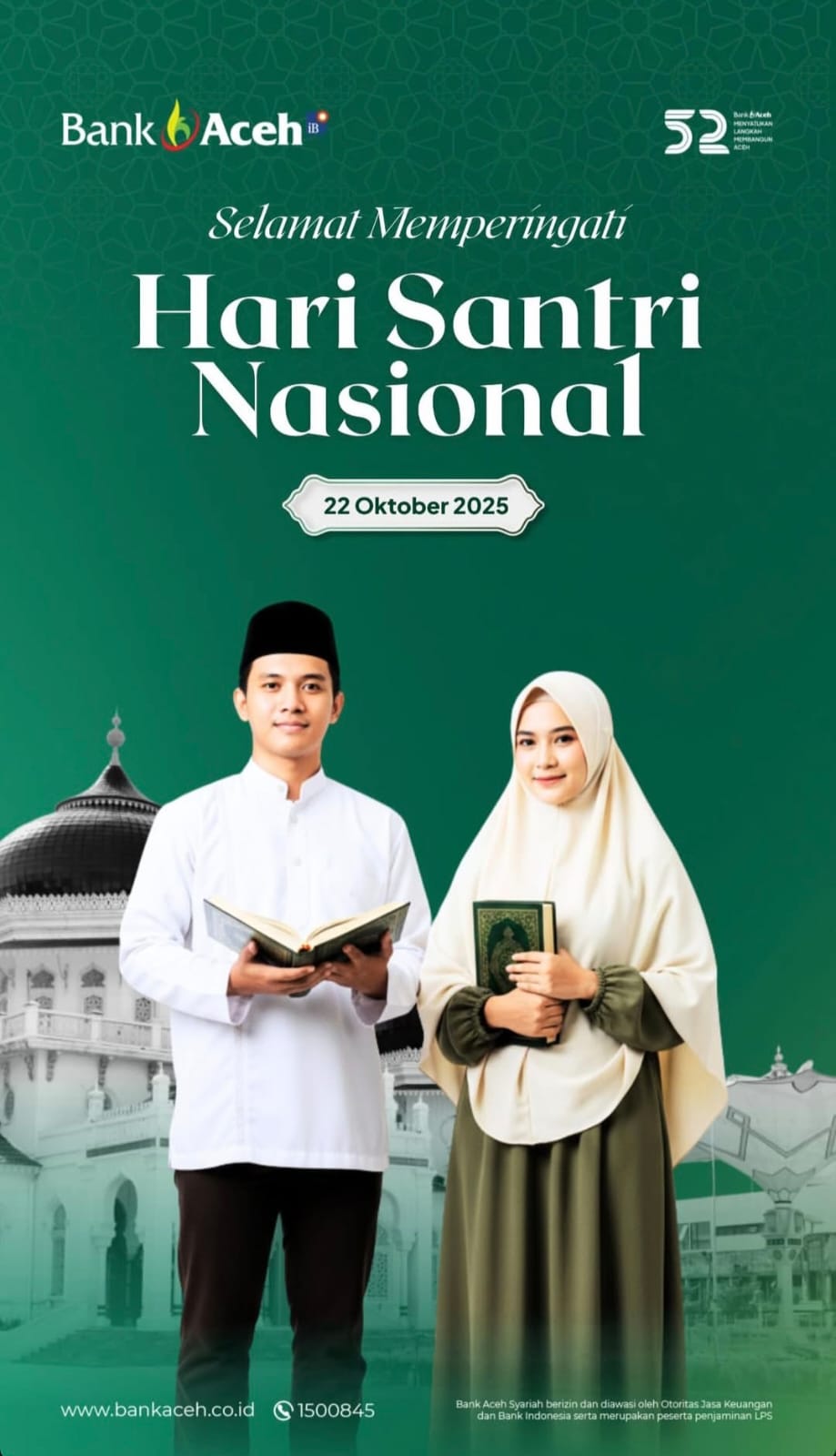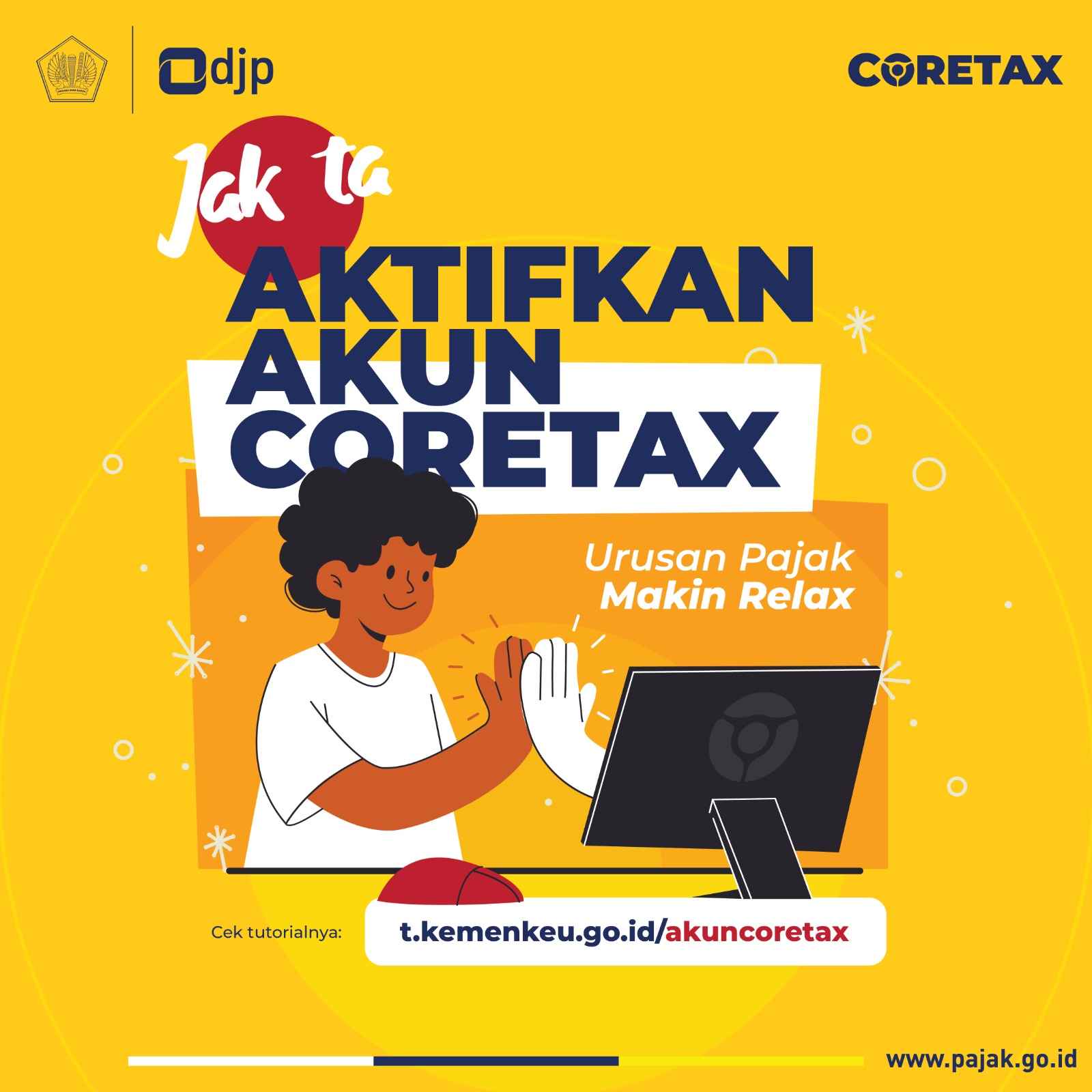Oleh: Yohandes Rabiqy
Masuknya 250 ton beras ke Sabang pada akhir 2025 bukan sekadar “kekeliruan prosedur” seperti yang coba diredam sejumlah pihak. Peristiwa ini justru membuka tabir betapa rapuhnya tata kelola administratif lembaga kawasan yang selama bertahun-tahun merasa memiliki otonomi super—bahkan seolah berdiri di atas kewenangan nasional. Sorotan publik pun mengarah pada Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), lembaga yang mengelola salah satu zona bebas paling strategis di Indonesia, namun gagal memegang prinsip dasar administrasi: kehati-hatian dan verifikasi.
Faktanya sederhana: 24 Oktober 2025, BPKS melalui UPPTSP menerbitkan izin pemasukan 250 ton beras dari Thailand. Beberapa hari kemudian kapal tiba, barang dibongkar, gudang terisi, dan semua tampak “legal” secara administratif. Namun semua itu runtuh ketika pemerintah pusat menegaskan bahwa tidak ada izin impor beras yang diterbitkan tahun ini. Rakornas Pangan pada 14 November 2025 bahkan secara eksplisit menolak usulan impor beras.
Dengan kata lain: izin BPKS bukan hanya keliru—tetapi bertabrakan langsung dengan kebijakan nasional.
Pada titik ini, pertanyaannya bukan lagi apakah izin itu legal. Pertanyaan yang lebih penting adalah: bagaimana mungkin sebuah lembaga kawasan bisa melakukan kesalahan fatal seperti ini?
BPKS mencoba berlindung pada argumen hukum: Sabang adalah wilayah di luar daerah pabean sesuai UU 37/2000, UU 11/2006, dan PP 83/2010. Barang yang masuk untuk kebutuhan Sabang, kata mereka, tidak dikenai tata niaga impor, bea masuk, PPN maupun PPnBM. Karena itu, pemasukan beras dianggap sah.
Namun penjelasan itu tidak menyingkirkan inti persoalan: status bebas pabean tidak menghapus kewajiban mematuhi aturan nasional mengenai barang larangan dan pembatasan (LARTAS).
Beras termasuk komoditas LARTAS—dengan pengaturan paling ketat.
UU 37/2000 Pasal 6 ayat (3), UU 7/2014 tentang Perdagangan, PP 71/2015 tentang Stabilitas Harga Pangan Pokok, serta regulasi teknis Bapanas dan Kementan semuanya sepakat pada satu prinsip:
wenang impor beras adalah kewenangan eksklusif pemerintah pusat.
Tidak ada ruang interpretasi. Tidak ada celah diskresi. Tidak ada “kedaulatan administratif lokal”.
Karena itu, izin yang diterbitkan BPKS hanya dapat dibaca sebagai kelalaian administratif tingkat berat—kesalahan yang menabrak struktur hierarki kewenangan dalam hukum administrasi Indonesia. Saat pusat menolak impor, daerah tidak boleh menerima. Saat pusat belum memutuskan, daerah wajib menunggu. Dan ketika komoditas adalah LARTAS, daerah tidak berhak menerbitkan izin apa pun.
Namun BPKS bertindak seolah kaidah itu tidak pernah ada.
Akibatnya, efek domino pun tak terhindarkan: kapal bergerak, beras masuk, karantina memeriksa, bongkar muat berlangsung, dan gudang terisi. Semua tampak legal hanya karena satu dokumen lokal yang seharusnya tidak pernah diterbitkan. Dalam literatur tata kelola publik, fenomena ini dikenal sebagai administrative laundering—proses ilegal yang terlihat sah karena dibingkai dokumen administratif yang salah paham terhadap batas kewenangannya.
Sementara itu, Kanwil Bea Cukai Aceh mempertegas bahwa prosedur BPKS dipenuhi pelanggaran. Dalam surat S-106/KBC.0101/2025, Bea Cukai menyatakan:
Dermaga CT-1 yang digunakan tidak memiliki Tempat Penimbunan Sementara (TPS) resmi.
Beras masuk dalam bentuk curah/non-kontainer yang seharusnya membutuhkan pengawasan khusus.
Beras sebagai barang konsumsi tidak boleh beredar keluar Sabang ke daerah pabean lainnya.
Pemerintah pusat tidak membuka impor umum beras 2025.
Kesimpulannya jelas: BPKS tidak hanya mengabaikan aturan vertikal (pusat), tetapi juga lalai memenuhi prosedur teknis horizontal (kepabeanan).
Di mata publik, yang terlihat adalah satu hal: barang sudah masuk sebelum kebijakan dipastikan, dan semua lembaga tampak saling menunggu klarifikasi. Yang tidak terlihat adalah retaknya koordinasi vertikal pusat–kawasan karena satu lembaga bertindak melebihi batas.
Inilah yang membuat kasus ini jauh lebih berbahaya daripada sekadar salah SOP. Ini adalah kegagalan struktural lembaga negara memahami posisinya dalam arsitektur hukum nasional. Ketika lembaga kawasan merasa lebih “berdaulat” daripada negara, maka negara kehilangan kendali atas komoditas strategisnya sendiri.
Dampaknya tidak kecil: beras ilegal mengancam petani lokal, mengganggu intervensi Bulog, menciptakan distorsi pasar, membuka peluang penyelundupan, melemahkan pengawasan keamanan pangan, hingga berpotensi merugikan negara dari sisi bea masuk dan pajak impor.
Karena itu, BPKS perlu dievaluasi secara menyeluruh. SOP wajib diperbaiki, mekanisme verifikasi pusat–kawasan harus dibuat mengikat, dan setiap izin terkait komoditas strategis harus mendapat persetujuan eksplisit kementerian teknis. Dan yang terpenting: BPKS harus mengingat bahwa kewenangan kawasan adalah delegasi negara, bukan hak istimewa.
Sabang boleh menjadi zona bebas ekonomi. Tapi Sabang tidak akan pernah menjadi zona bebas hukum.
Selama kelalaian administratif seperti ini dibiarkan, kasus serupa hanya menunggu waktu untuk terulang—dengan skala lebih besar, kerugian lebih mahal, dan kepercayaan publik yang semakin tipis.