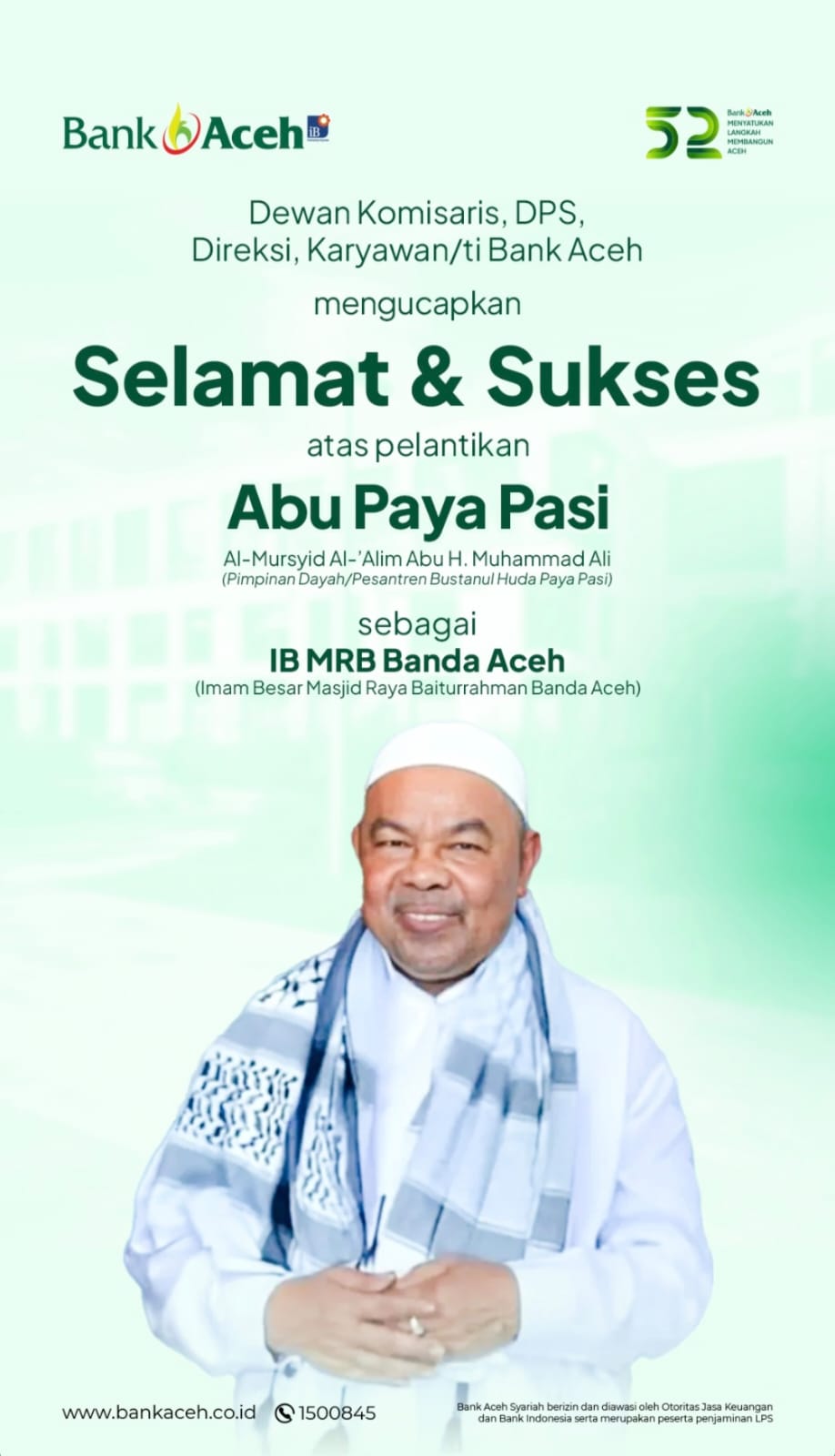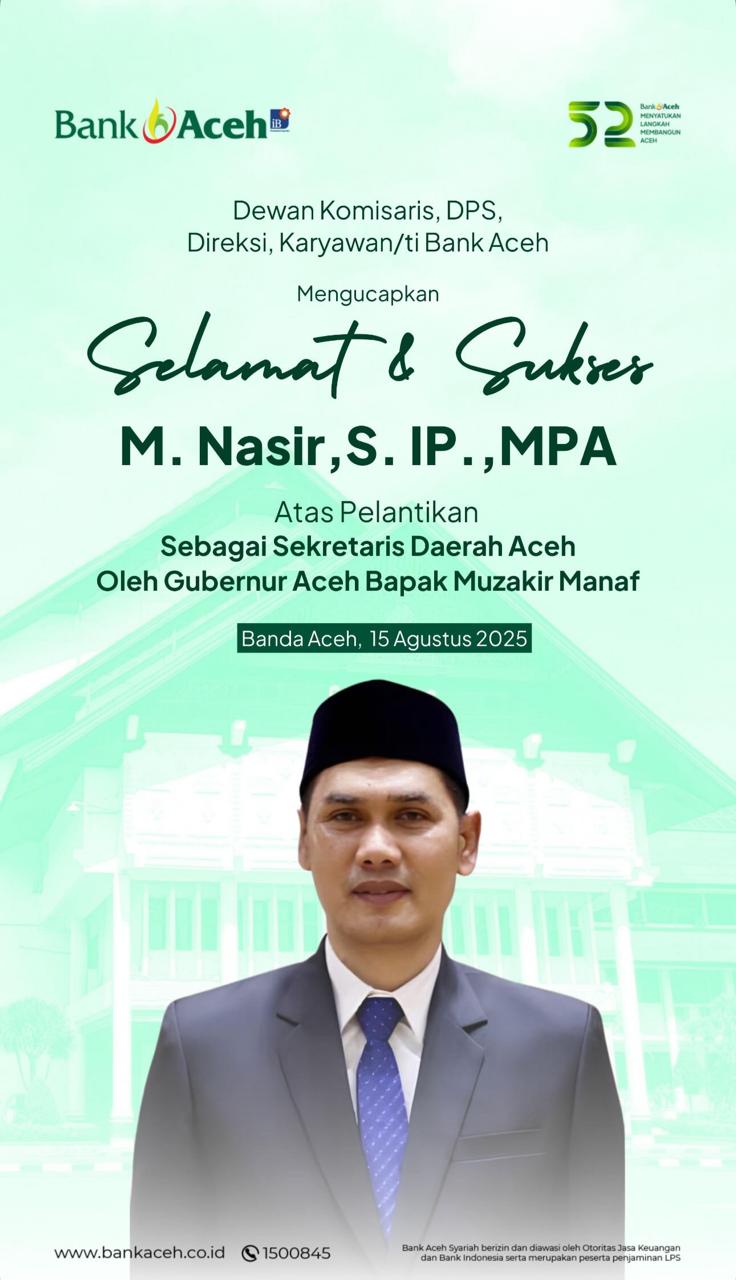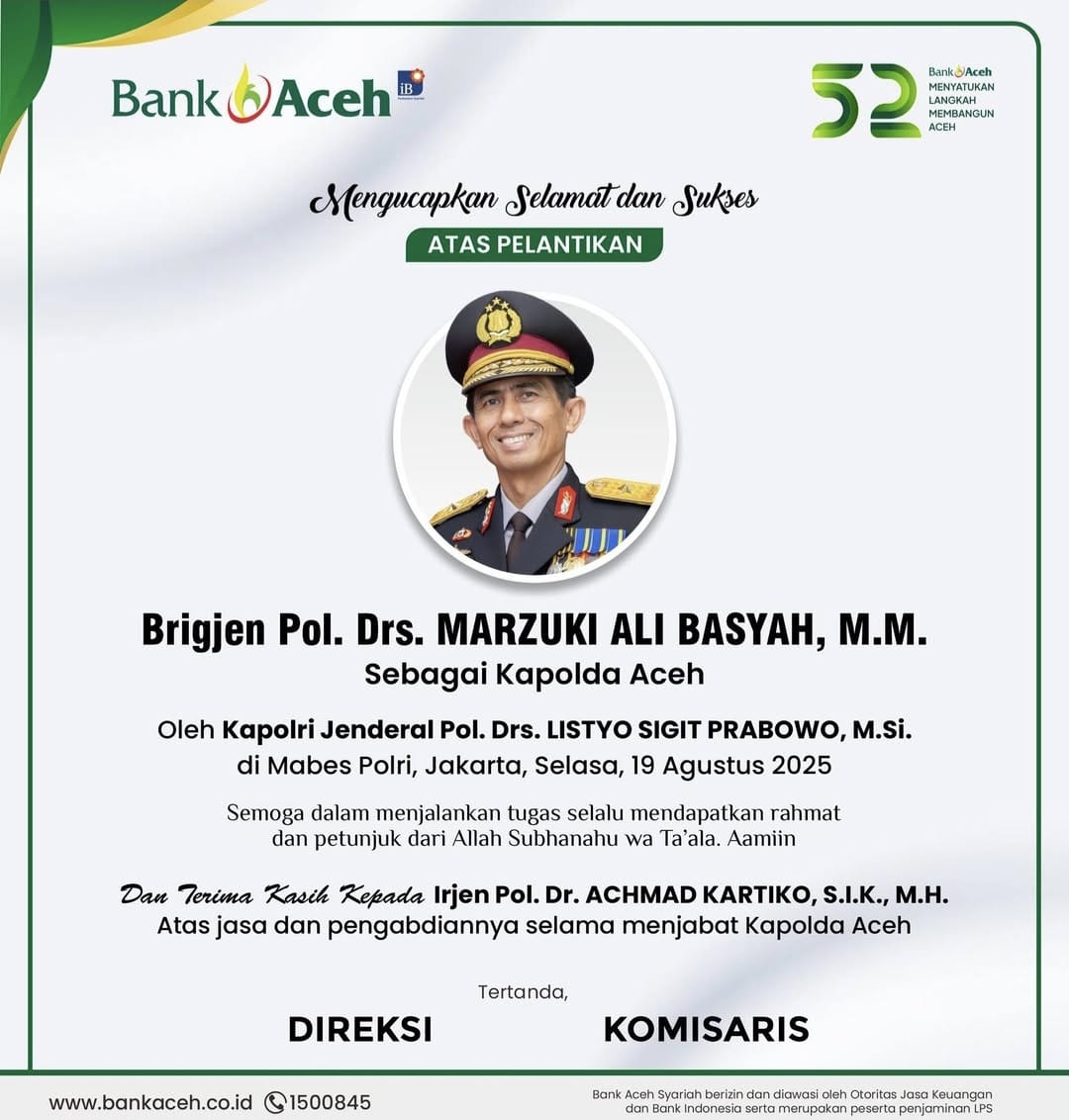SDT mengacu pada proses transisi demografi di Eropa Barat yang dimulai tahun 1965. Secara teoretis, SDT menjelaskan transisi menuju angka fertilitas di bawah tingkat penggantian (replacement rate).
Proses SDT ditandai beberapa gejala, tulis Saqib Fardan Ahmada, seperti perubahan norma keluarga, naiknya tren pergeseran dari pernikahan menjadi kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan), perubahan norma keluarga yang berpusat pada anak menjadi keluarga berpusat pada diri sendiri/pasangan, hingga munculnya variasi tipe rumah tangga (RT).
Dalam hal perubahan norma keluarga, hal yang umum terjadi ialah munculnya dual earner family (keluarga dengan dua pencari nafkah).
Ini sejalan dengan tren kenaikan angka partisipasi kerja perempuan (mandiri).
Selain itu, muncul pula perubahan dalam format keluarga, ditandai munculnya ekonomi RT baru (new household economics/NHE).
NHE mengasumsikan permintaan RT untuk memiliki anak ditentukan oleh biaya atau opportunity cost dalam membesarkan anak dan tingkat pendapatan keluarga.
Untuk menjelaskan pengaruh SDT dalam konteks Indonesia, Utomo dkk (2022), seperti dikutip Saqib Fardan Ahmada, menemukan proses SDT di Indonesia tengah terjadi dengan melihat fertilitas di bawah replacement rate di beberapa provinsi, antara lain DKI Jakarta, DIY, Jawa Timur dan Banten.
Selain itu, terdapat peningkatan usia saat menikah pertama, nonpernikahan, dan tingkat perceraian serta pertumbuhan keberagaman dalam tipe RT.
Contohnya, dalam konteks variasi tipe RT, data 1993-2020 mengungkapkan adanya pergeseran.
Terjadi peningkatan proporsi RT yang terdiri atas pasangan tanpa anak dari 7,43 persen pada 1993 menjadi 9,4 persen pada 2020.
Demikian pula, RT satu orang juga mengalami tren meningkat, dari 6,03 persen menjadi 8,03 persen.
Sebaliknya, tipe RT yang dominan, yaitu pasangan dengan anak, berkurang dari 55,14 persen menjadi 50,48 persen.
Meski demikian, menurut Saqib Fardan Ahmada, perlu dicatat bahwa secara geografis dan demografis Indonesia memiliki ciri tingkat keberagaman yang tinggi.