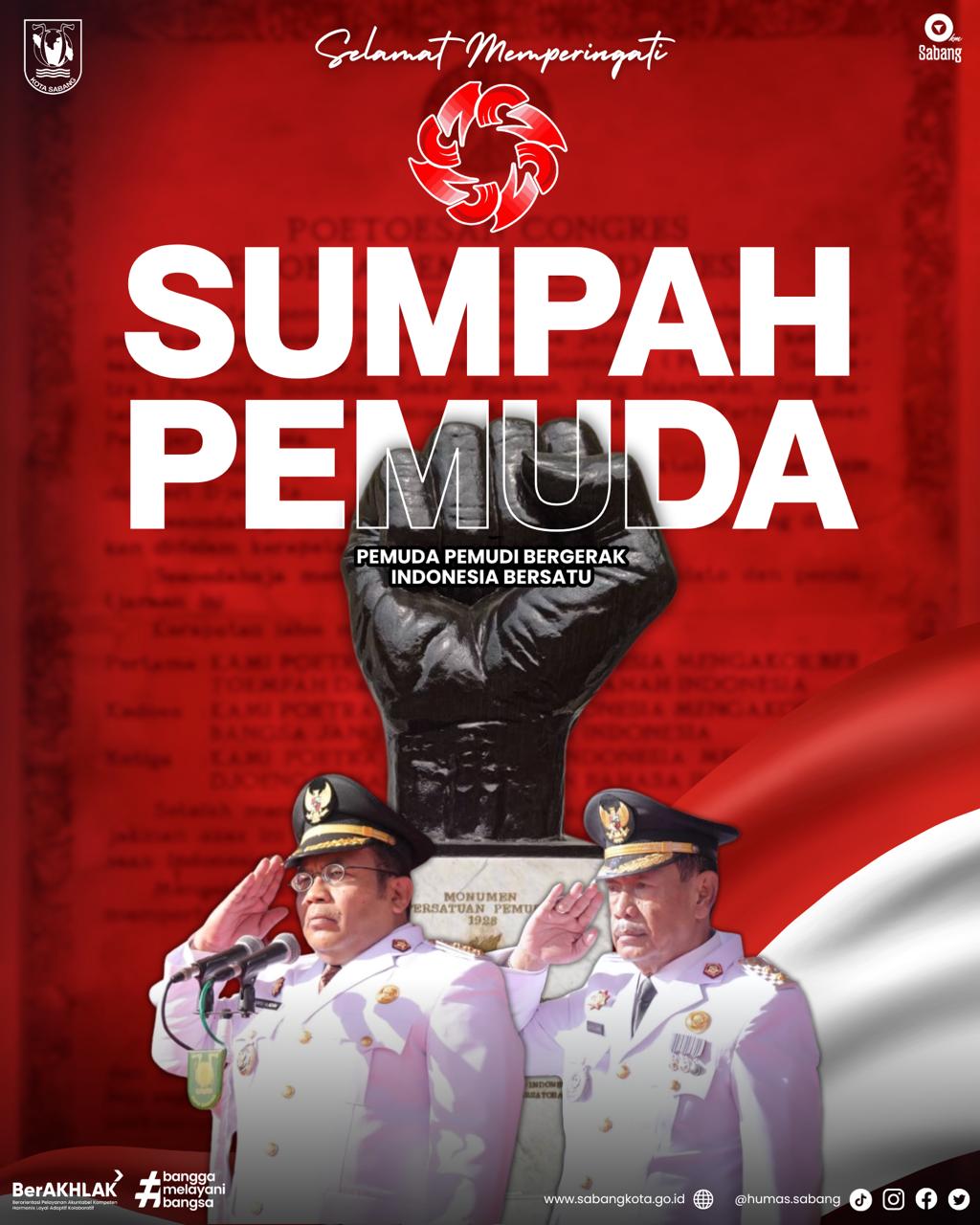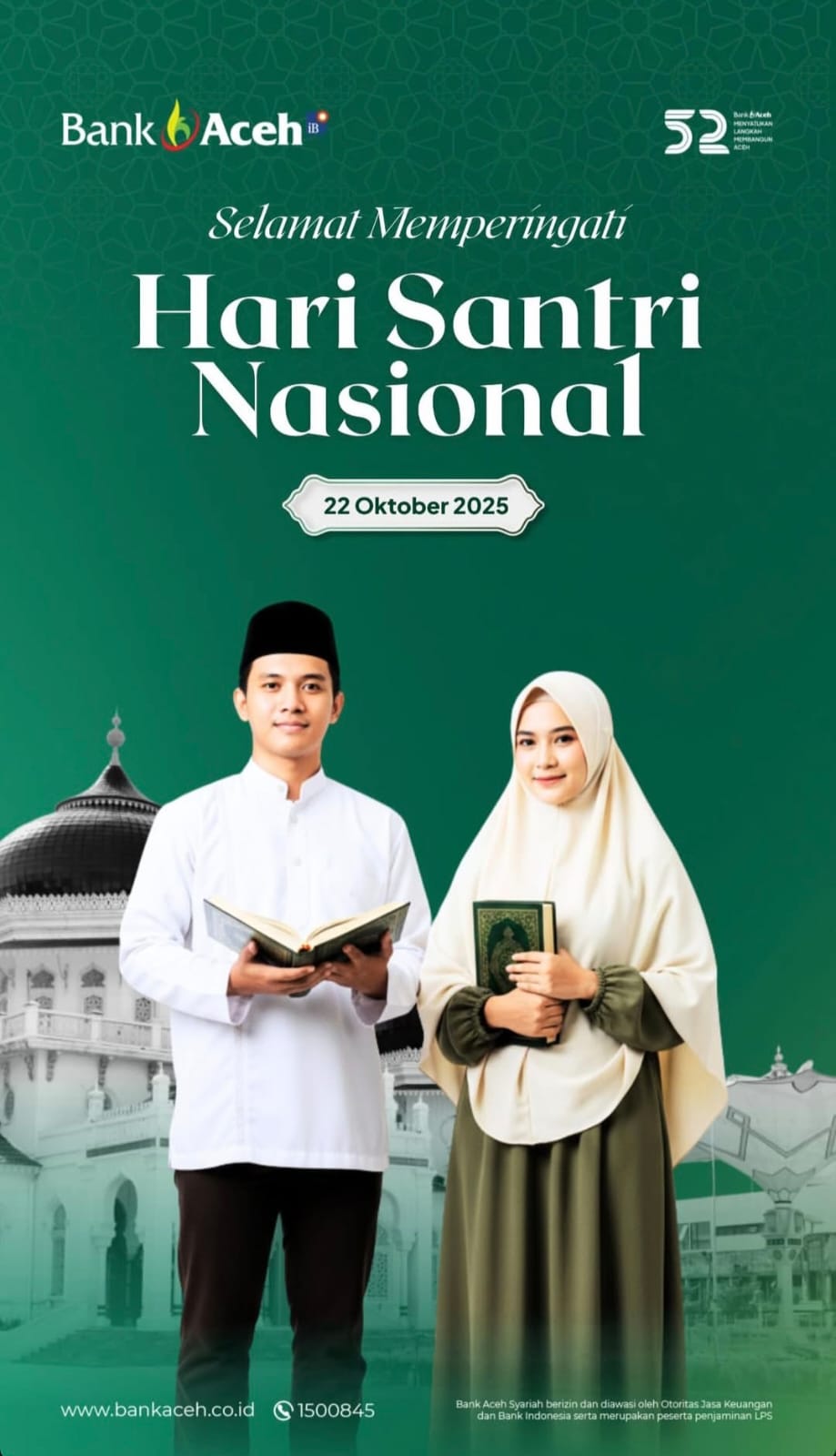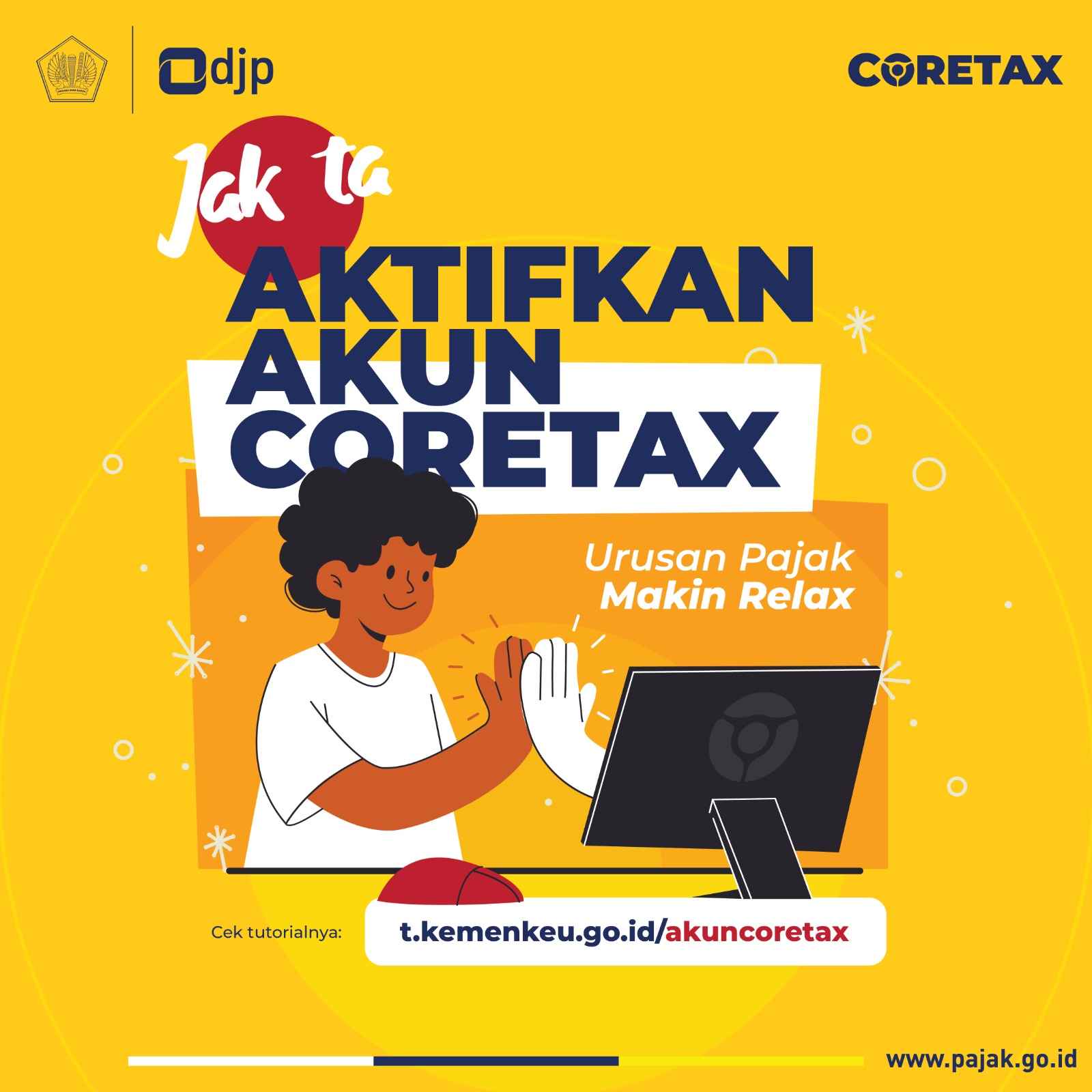Penulis: Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)
INDONESIA hari ini sedang berdiri di persimpangan yang ganjil, di satu sisi kita mengaku sebagai negara hukum yang demokratis, di sisi lain hukum sering tampil sebagai alat kekuasaan.
Kasus penetapan Roy Suryo dan tujuh orang penggugat ijazah bekas Presiden Joko Widodo sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya kembali menegaskan luka lama itu, bahwa hukum di negeri ini masih mudah dibelokkan arah oleh kepentingan politik.
Delapan orang dinyatakan tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik dan manipulasi data. Polisi menyebut ada ratusan saksi dan ahli yang diperiksa, serta lebih dari tujuh ratus barang bukti disita.
Dari luar, proses itu tampak megah dan formal. Tapi di mata publik, yang muncul justru keraguan, mengapa hukum begitu cepat menindak pengkritik, namun begitu lamban menelusuri tuduhan yang ditujukan kepada penguasa?
Mengapa hukum yang katanya netral justru terasa memihak pada yang kuat?
Fenomena ini memperlihatkan bahwa reformasi hukum yang diimpikan sejak 1998 masih jauh dari selesai. Dulu, kita menumbangkan rezim otoriter dengan harapan melahirkan hukum yang adil dan berpihak pada rakyat.
Dua puluh lima tahun kemudian, semangat itu seperti terperangkap dalam ruang gelap kekuasaan. Polri yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, justru kerap dipersepsikan sebagai pelayan kepentingan elite.
Kritik terhadap presiden, pejabat, atau institusi negara kini terasa semakin berisiko, seolah negara kembali menjadi menara gading yang tak boleh disentuh.
Dalam filsafat hukum, keadilan adalah nurani bangsa. Tanpa keadilan, negara kehilangan ruhnya. Plato dalam Republic menyebut keadilan sebagai harmoni antara kekuasaan dan kebijaksanaan, sementara Mahatma Gandhi pernah mengingatkan bahwa hukum tanpa moralitas hanya akan melahirkan tirani yang sah secara legal, tetapi busuk secara nurani.
Di Indonesia, nurani hukum itu kerap pingsan, ia hidup di teks undang-undang, tapi mati dalam praktik.
Penerapan pasal-pasal karet dalam KUHP baru, yang memungkinkan seseorang dipidana karena dianggap menghina presiden, menambah kekhawatiran publik.
Kritik yang seharusnya menjadi vitamin demokrasi, kini justru dianggap racun bagi kekuasaan. Padahal dalam demokrasi yang sehat, rakyat berhak memeriksa, mempertanyakan, dan bahkan menggugat penguasa.
Presiden bukan dewa, melainkan pejabat publik yang mandatnya berasal dari rakyat. Ketika kritik dipidana, yang mati bukan hanya kebebasan, tapi juga akal sehat bangsa.
Sejarah menunjukkan bangsa ini hanya besar ketika keberanian rakyat berjalan beriring dengan kebijaksanaan pemimpin. Di masa perjuangan kemerdekaan, hukum adalah alat pembebasan, bukan alat penindasan. Para pendiri bangsa menulis Pancasila bukan untuk melindungi kekuasaan dari kritik, tetapi untuk menjamin martabat manusia agar tak lagi diinjak oleh kuasa.
Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, adalah pesan agar hukum tidak kehilangan hati. Sebab tanpa hati, keadilan hanyalah prosedur, bukan kebijaksanaan.
Namun hari-hari ini, hukum kerap hadir tanpa hati. Ia menatap rakyat dengan mata dingin dan berlidah basa-basi. Kasus kriminalisasi terhadap pengkritik kekuasaan hanya menambah jarak antara rakyat dan negara.
Rakyat kecil makin takut bersuara, media tertekan untuk berhati-hati, dan akademisi pun mulai waspada dalam bicara. Padahal bangsa yang besar lahir dari ruang perbedaan, bukan dari keheningan yang dipaksakan.
Survei lembaga publik belakangan menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum masih di bawah 60 persen.
Artinya, lebih dari separuh rakyat Indonesia tidak yakin hukum akan berpihak pada kebenaran ketika berhadapan dengan kekuasaan. Ini adalah tanda bahaya bagi demokrasi.
Negara yang rakyatnya kehilangan kepercayaan pada hukum, akan mudah tergelincir ke dalam kekacauan moral dan politik.
Kita tentu tidak menolak proses hukum terhadap siapa pun yang bersalah. Tapi keadilan tidak boleh dipertontonkan setengah hati. Jika aparat cepat bertindak terhadap pengkritik, maka mereka jug