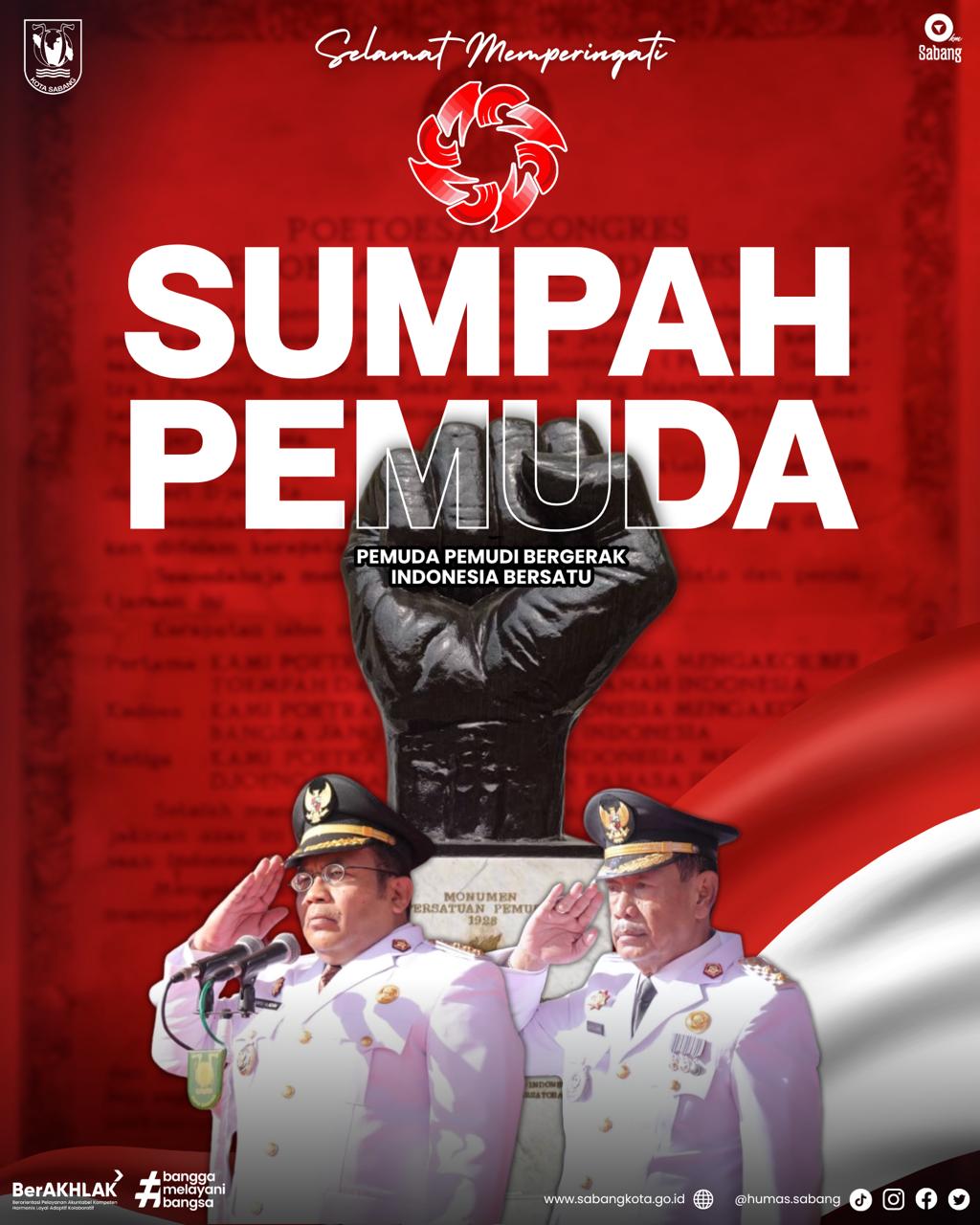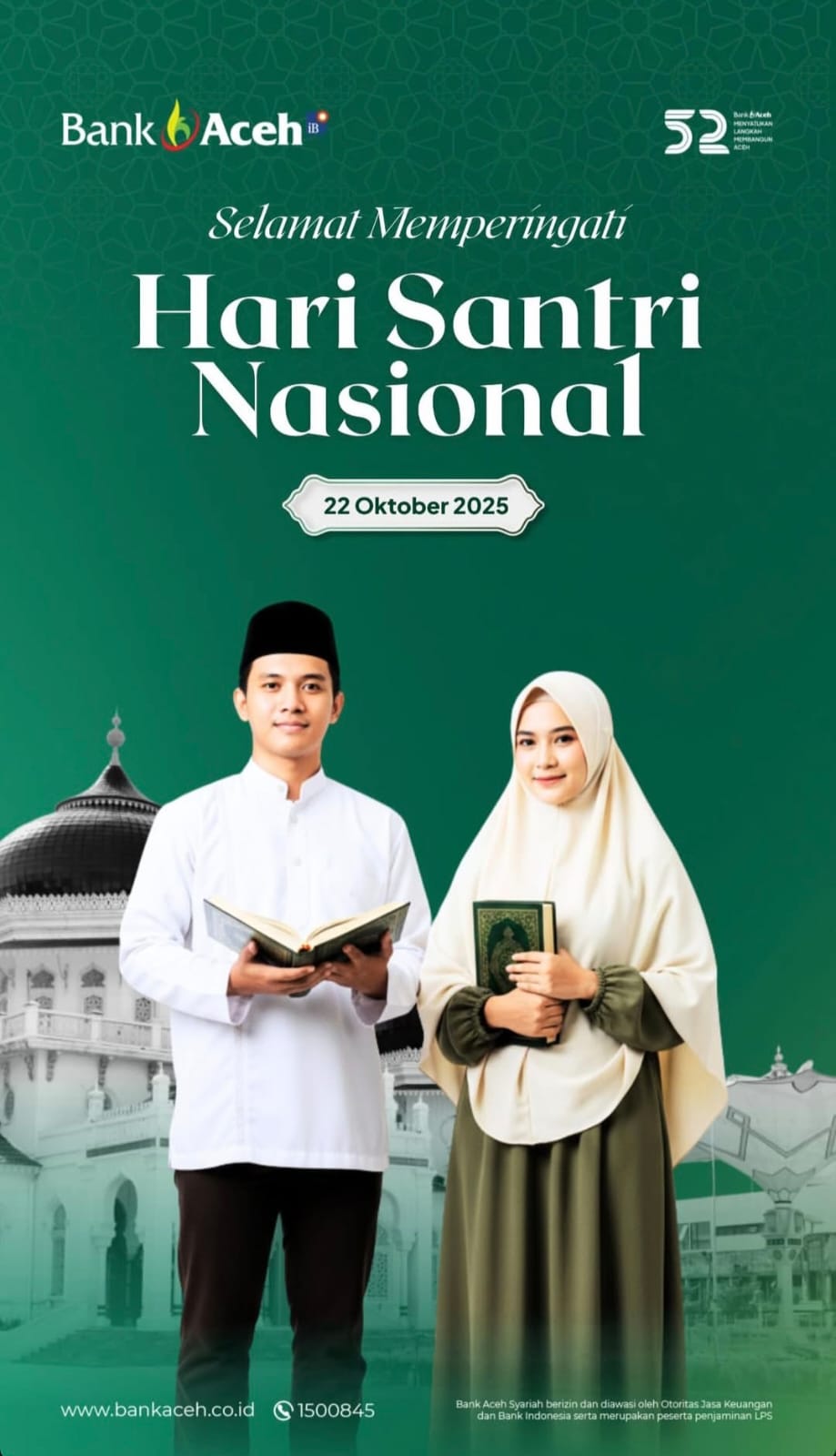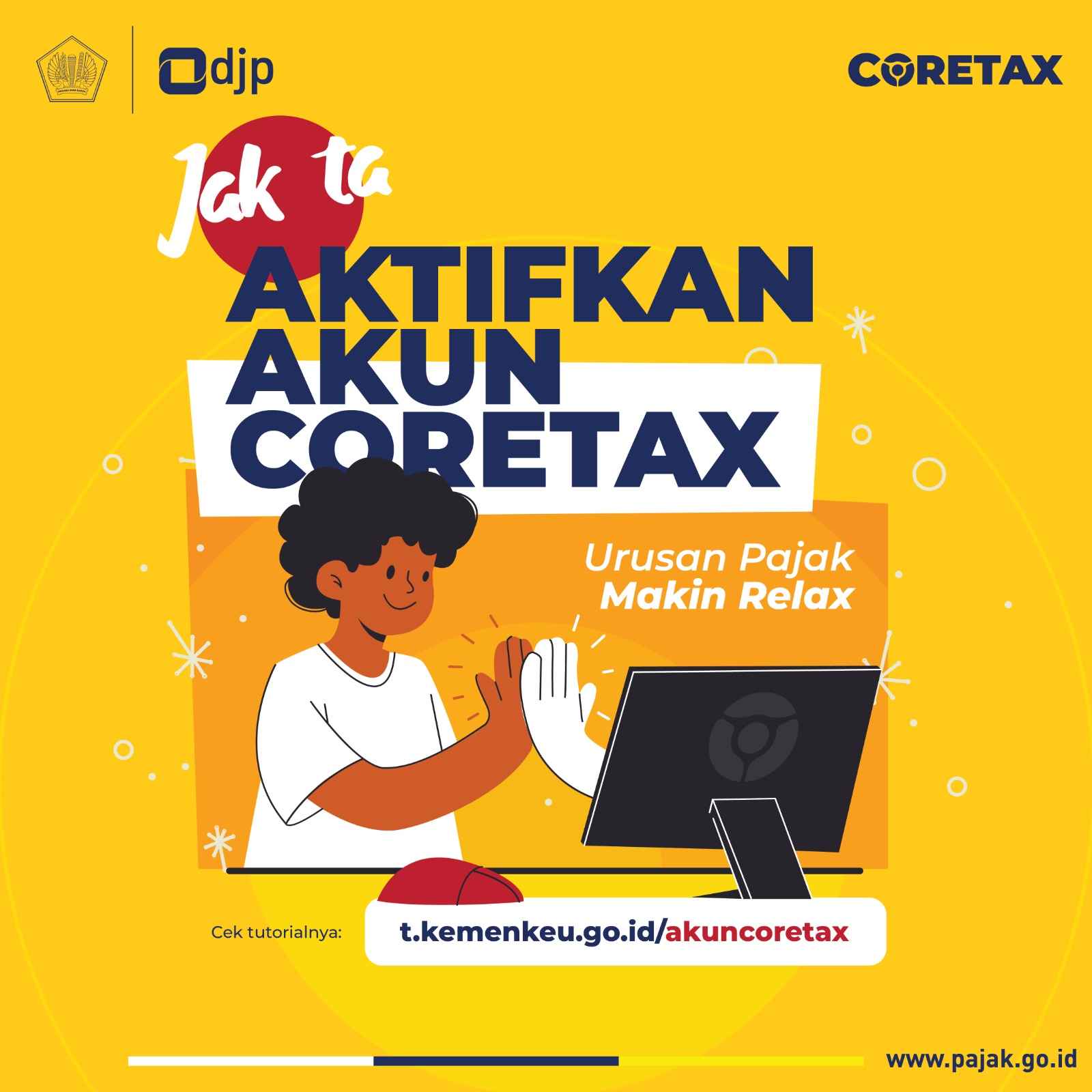Infoaceh.net – Ketika seorang calon kepala daerah mengantongi dukungan besar dan berjuang merebut kursi eksekutif, satu hal yang kerap terlupakan adalah biaya politik yang harus dibayar setelah kemenangan diraih.
Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid, memperlihatkan wajah gelap dari praktik politik daerah yang mahal dan sarat kepentingan. Proyek dan anggaran yang semestinya menjadi instrumen pembangunan justru beralih fungsi menjadi jalur pengembalian modal politik.
Menurut keterangan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), modus yang digunakan dalam kasus Abdul Wahid adalah penambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Sebagian dana dari proyek-proyek tersebut diduga disetor kepada kepala daerah sebagai “jatah preman sekian persen”, ungkap juru bicara KPK.
KPK menyita uang tunai dalam berbagai mata uang dengan total sekitar Rp1,6 miliar sebagai bukti awal. Nilai itu diyakini hanya sebagian kecil dari rangkaian aliran dana yang terjadi secara sistematis. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa jabatan gubernur di Riau bukan hanya posisi publik, tetapi juga investasi politik yang harus segera memberi imbal hasil.
Para pakar menilai, biaya kampanye yang tinggi mendorong pejabat terpilih untuk mencari cara menutup kembali pengeluaran politik mereka. Dengan kontrol besar terhadap anggaran daerah, posisi gubernur dan bupati menjadi sangat strategis, bukan hanya untuk pelayanan publik, tetapi juga untuk kepentingan bisnis dalam proyek-proyek pemerintah.
“Ketika kursi pemerintahan menjadi instrumen bisnis, maka batas antara kepentingan publik dan pribadi kabur,” ujar seorang peneliti politik lokal. Pejabat yang seharusnya menjadi pengawas penggunaan anggaran justru berubah menjadi titik akhir transaksi proyek, bukan pelayan masyarakat.
Dampaknya jelas: kualitas pelayanan publik menurun, proyek menjadi mahal dan tidak efisien, serta masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan. Ketika motivasi pembangunan bergeser dari kebutuhan rakyat ke kebutuhan balik modal politik, demokrasi daerah berubah menjadi pasar kekuasaan.
Fenomena ini juga menciptakan siklus korupsi politik yang berulang. Pejabat terpilih bukan karena visi pelayanan publik, tetapi karena kemampuan finansial dan jaringan bisnis yang kuat. Akibatnya, korupsi bukan lagi kasus individual, melainkan penyakit sistemik dalam tubuh pemerintahan daerah.
Untuk memutus siklus tersebut, reformasi harus menyasar akar masalahnya: transparansi dana kampanye, pengawasan internal pemerintah yang kuat dan independen, serta pendidikan integritas di semua tingkatan birokrasi. Dana publik harus diawasi ketat, terutama dalam pengadaan barang, jasa, dan proyek infrastruktur yang sering menjadi celah korupsi.
Kasus Abdul Wahid di Riau bukan sekadar berita kriminal. Ia adalah cermin dari betapa rapuhnya moralitas politik lokal ketika jabatan publik disamakan dengan peluang bisnis. Selama sistem politik dan anggaran tidak direformasi secara menyeluruh, kursi pemerintahan daerah akan terus menjadi arena pengembalian investasi politik — bukan tempat melayani rakyat.